
Bandung, Sebaran.com — Dalam senyap kampus yang dikenal sebagai gudang guru, riak polemik justru muncul dari jantung kebijakan: pemilihan rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
Alih-alih menjadi selebrasi intelektual dan demokrasi akademik, proses ini justru memantik perdebatan hukum yang tak bisa diabaikan. Pasalnya, Peraturan Majelis Wali Amanat (MWA) UPI Nomor 1 Tahun 2025 dianggap menabrak konstitusi internal perguruan tinggi itu sendiri—Statuta UPI.
Masalah bermula dari Pasal 17 peraturan tersebut yang menyatakan bahwa setiap anggota MWA, termasuk Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, hanya memiliki satu suara. Sebuah penyederhanaan yang secara langsung bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (4) Statuta UPI berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2014, yang menggariskan bahwa suara Menteri setara dengan 35 persen dari total hak suara.
“Ini bukan hanya soal jumlah suara, tapi soal penghormatan terhadap peran negara dalam pendidikan tinggi,” ungkap Elly Malihah, guru besar Sosiologi Pendidikan sekaligus anggota Senat Akademik UPI.
Bagi Elly, aturan baru ini berpotensi mereduksi posisi negara menjadi sekadar pengamat dalam proses strategis pemilihan rektor. Padahal, Menteri bukan sekadar figur simbolik, melainkan entitas dengan fungsi korektif, bahkan penyelesai konflik sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 Ayat (3) Statuta UPI.
“Kalau suaranya disamakan, lalu bagaimana dengan peran Menteri sebagai pengambil keputusan terakhir saat kampus buntu dalam kebijakan? Ini inkonsistensi yang bisa berakibat panjang,” tandasnya.
Ia mengingatkan kembali pada kasus di Universitas Sebelas Maret (UNS), di mana hasil pemilihan rektor dibatalkan oleh Kementerian karena dianggap melanggar prinsip transparansi dan keadilan. “UPI tidak boleh terjebak dalam lubang yang sama. Ini bukan sekadar urusan siapa yang menang, tapi bagaimana caranya dipilih,” tegas Elly.
Lebih jauh, ia menyebut penghilangan hak suara 35 persen bagi Menteri sebagai bentuk reduksi politik yang mengabaikan realitas UPI sebagai perguruan tinggi negeri. “Negara punya saham, negara punya tanggung jawab, dan negara semestinya punya suara proporsional,” ujarnya.
Kritik ini bukan provokasi. Justru ia lahir dari semangat menjaga marwah kampus. Jika tidak, jargon yang dibanggakan MWA seperti “values for value, full commitment, no conspiracy” hanya akan tinggal sebagai etalase kosong di brosur, tak berjejak dalam realita.
Kini, pilihan ada pada MWA. Akankah mereka membuka telinga terhadap suara akal sehat, atau memilih bergeming dalam keheningan administratif yang penuh risiko? (*)
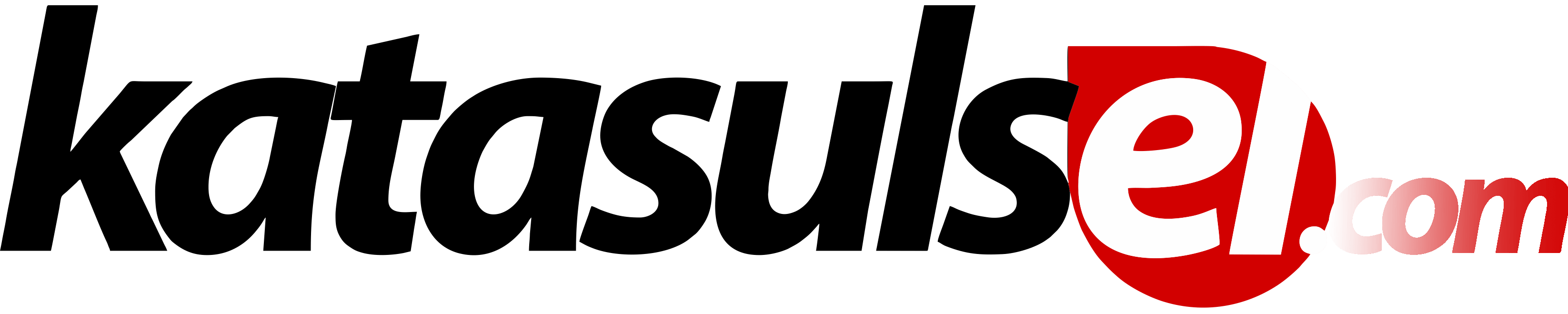








Tinggalkan Balasan